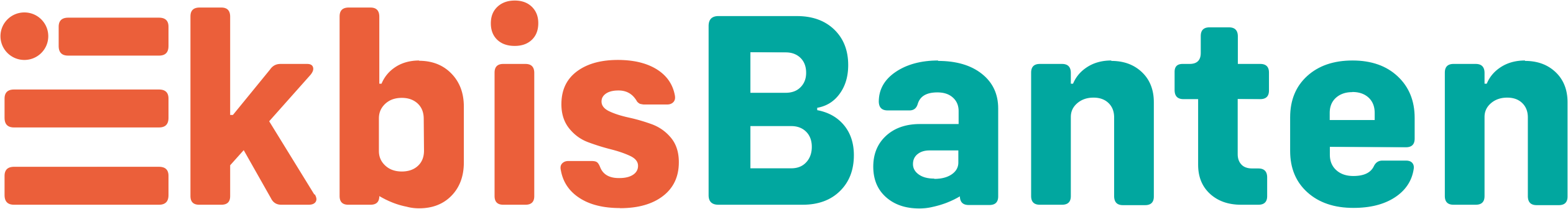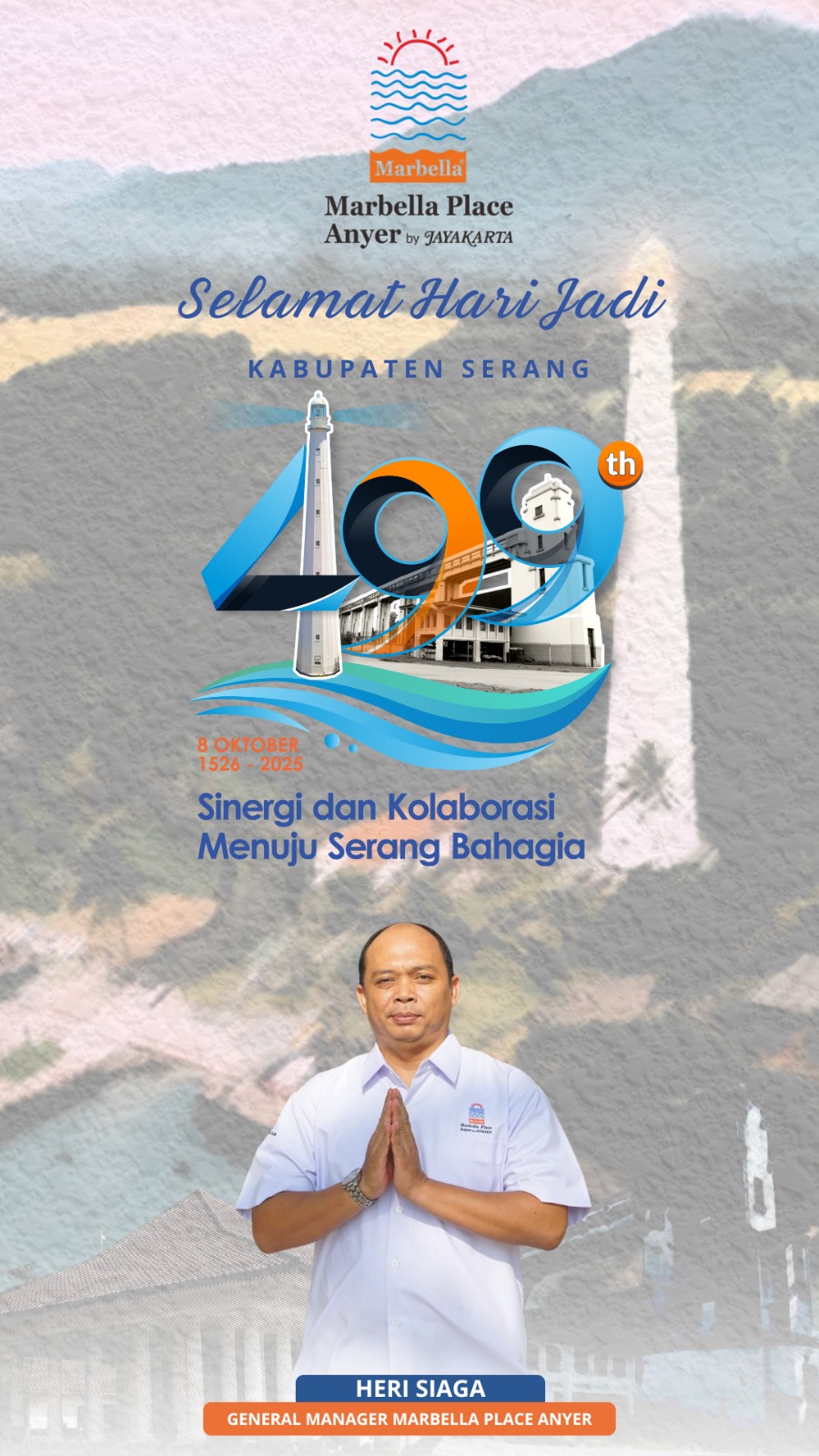Esti Aryani, S.H, M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Nama Bjorka mungkin sudah menjadi legenda di dunia siber Indonesia, sosok atau kelompok misterius yang mengaku membocorkan data publik dari berbagai instansi negara, pejabat, dan perusahaan besar. Penangkapannya atau tepatnya klaim aparat bahwa mereka telah mengidentifikasi pelaku selalu menjadi berita besar. Namun, di balik sorotan publik terhadap siapa di balik nama itu, terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting: apa makna hukum dan keadilan dari penangkapan seseorang yang dituduh sebagai peretas di tengah carut-marutnya tata kelola data negara?
Fenomena Bjorka tidak bisa dipahami sekadar sebagai kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia adalah gejala sosial dari krisis kepercayaan publik terhadap keamanan digital negara. Jika data pribadi warga bisa dengan mudah bocor dari lembaga pemerintah, lalu masyarakat justru tahu kebenarannya dari seorang “peretas”, maka yang perlu diadili bukan hanya peretasnya, tetapi juga sistem yang lalai melindungi kedaulatan data publik.
Hukum Siber dan Batas Kekuasaan Negara
Secara hukum, tindakan peretasan atau pembobolan sistem elektronik tanpa izin memang termasuk tindak pidana. Pasal 30 dan 32 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, merusak, atau menyebarkan informasi elektronik milik pihak lain dapat dikenai pidana penjara hingga 8 tahun dan denda hingga 8 miliar rupiah.
Namun, hukum pidana tidak hidup dalam ruang hampa. Ia harus ditegakkan dalam bingkai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Artinya, meskipun negara berhak menindak pelaku kejahatan digital, cara penegakan hukumnya tidak boleh mengabaikan transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Penangkapan tidak boleh menjadi simbol kekuasaan yang menakut-nakuti, tetapi harus menjadi langkah hukum yang membangun kepercayaan publik terhadap keadilan.
Dalam kasus Bjorka, penegakan hukum sering kali tampak lebih seperti reaksi politis ketimbang prosedur hukum yang matang. Publik kerap dibuat bingung oleh pengumuman yang prematur dari “Bjorka sudah ditangkap” hingga “yang ditangkap hanyalah penyebar informasi sekunder.”
Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara masih kesulitan menegakkan hukum di ruang digital yang begitu cair dan anonim.
Antara Hacker dan Whistleblower
Dalam diskursus hukum siber internasional, ada garis tipis antara hacker dan whistleblower.
Hacker biasanya digambarkan sebagai pelaku yang menembus sistem tanpa izin dan berpotensi merusak atau mencuri data. Namun whistleblower sering kali justru membuka kebobrokan sistem demi kepentingan publik.
Pertanyaannya, di mana posisi Bjorka dalam dua kategori ini? Apakah ia sepenuhnya pelaku kriminal, ataukah ia sekadar cermin dari sistem yang gagal melindungi hak digital warga negara?
Hukum pidana siber di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pembedaan moral ini. Setiap tindakan akses ilegal langsung dikategorikan sebagai kejahatan, tanpa mempertimbangkan motif dan konteks sosialnya. Padahal, dalam prinsip hukum modern, niat dan tujuan pelaku (mens rea) adalah unsur yang penting untuk menilai kadar kesalahannya.
Jika motivasi pelaku adalah mengungkap kelemahan sistem demi mendorong reformasi keamanan siber, maka pendekatan hukum yang semata-mata represif justru bisa membungkam kritik dan inovasi sosial. Negara perlu berhati-hati agar tidak mengkriminalisasi kritik dengan label “peretasan.”
Kedaulatan Siber dan Lemahnya Infrastruktur Hukum Digital
Kasus Bjorka juga memperlihatkan satu hal mendasar yakni Indonesia belum memiliki kedaulatan digital yang kokoh. Kebocoran data bukan hal baru mulai dari data e-KTP, SIM card, sampai data kependudukan, semuanya pernah dijual di forum gelap (dark web). Namun, penegakan hukum terhadap lembaga yang lalai menjaga data publik hampir tidak pernah terdengar.
Hukum kita keras kepada individu peretas, tetapi lembek terhadap kelalaian institusi negara.
Padahal Pasal 58 dan 59 UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa pengendali data (termasuk instansi pemerintah) wajib menjaga keamanan data pribadi. Pelanggaran atas kewajiban itu juga dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Jika negara menuntut rakyat untuk taat hukum digital, maka negara juga wajib memberi contoh dengan menjadi pelindung data yang terpercaya.
Menangkap pelaku peretasan memang perlu, tetapi jauh lebih penting memastikan bahwa tidak ada lagi alasan bagi siapa pun untuk “membocorkan” data karena sistem keamanan yang buruk.
Transparansi Penegakan dan Akuntabilitas Publik
Dalam konteks demokrasi digital, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan, bukti apa yang digunakan, dan apakah hak-hak tersangka dijamin secara hukum. Kita tidak boleh mengulangi pola lama di mana penegakan hukum menjadi sarana pencitraan politik. Penangkapan seorang yang dituduh sebagai Bjorka seharusnya bukan akhir cerita, tetapi awal reformasi keamanan siber nasional.
Negara perlu menjadikan kasus ini momentum untuk memperbaiki tata kelola data, memperkuat literasi digital aparat, dan membangun kepercayaan publik bahwa hukum siber ditegakkan untuk semua, bukan hanya untuk yang lemah.
Membangun Hukum Siber yang Adil dan Berdaulat
Kasus Bjorka adalah cermin dari dua hal sekaligus yakni ketanggapan hukum dan kerentanan negara.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa di balik jargon “transformasi digital,” masih ada pekerjaan rumah besar yaitu memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir ketika data bocor, tetapi juga ketika rakyat kehilangan privasi dan rasa aman. Hukum siber di masa depan tidak boleh berhenti pada pendekatan represif. Ia harus menggabungkan perlindungan, pendidikan, dan keadilan. Menangkap pelaku peretasan boleh, tetapi membangun sistem yang membuat peretasan tak lagi diperlukan adalah tujuan yang lebih mulia. Karena pada akhirnya, kedaulatan digital bukan tentang menaklukkan hacker, tetapi tentang menegakkan kepercayaan rakyat terhadap negara di dunia maya.
Penulis: Esti Aryani, S.H, M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi)